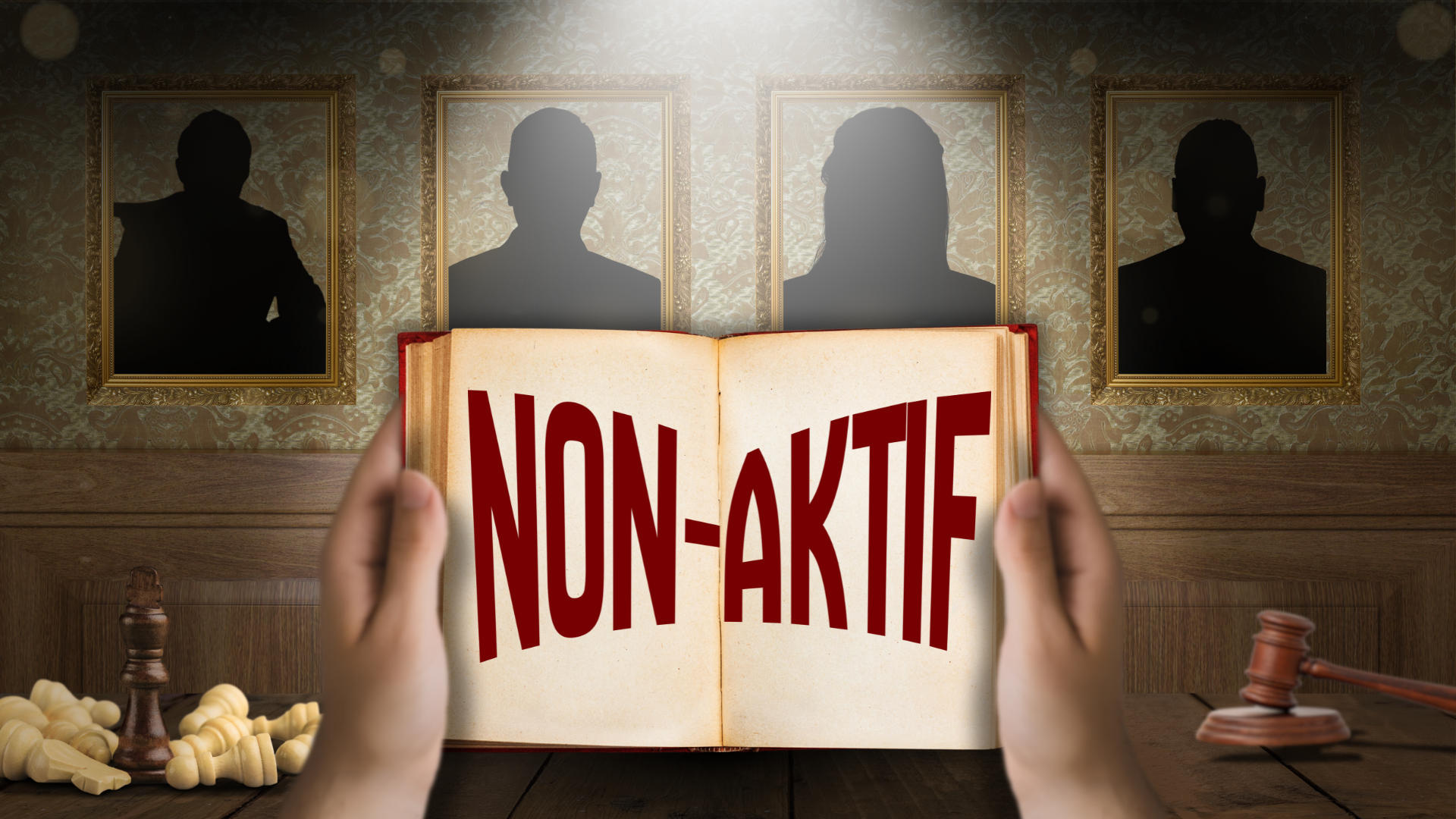Kajian mengenai penonaktifan dan pemberhentian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan topik yang krusial dalam hukum tata negara karena menyangkut hak konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta prinsip kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat memegang peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan keanggotaan harus memperhatikan prinsip due process of law. Dalam praktik ketatanegaraan, istilah “penonaktifan” DPR kerap digunakan, terutama oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebagai bagian dari sanksi etik terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Akan tetapi, istilah penonaktifan tidak memiliki dasar konstitusional maupun yuridis formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Undang-Undang MD3). Penonaktifan bersifat administratif sehingga anggota yang dinonaktifkan tetap memegang status dan hak-haknya sebagai anggota, namun untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas-tugas kedewanan. Hal ini menimbulkan perdebatan karena sebagian pihak memandang penonaktifan sebagai bentuk “pemberhentian” yang tidak melalui mekanisme yang sah, padahal kursi DPR merupakan mandat rakyat yang hanya dapat dicabut melalui prosedur yang jelas.
Berbeda dengan penonaktifan, mekanisme pemberhentian yang sah secara hukum adalah Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang memiliki dasar konstitusional kuat. Pasal 22B UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa anggota DPR yang berhenti sebelum habis masa jabatannya akan digantikan oleh calon pengganti yang berasal dari partai politik yang sama. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 239–240 Undang-Undang MD3 yang menyebutkan bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dilakukan karena anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, melanggar kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dilakukan secara berlapis: partai politik terlebih dahulu mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) kepada pimpinan DPR, kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Presiden, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nama calon pengganti berdasarkan perolehan suara Pemilu, dan terakhir anggota pengganti dilantik melalui rapat paripurna DPR. Proses berlapis ini dirancang untuk menjamin perlindungan hak konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mencegah pemberhentian yang sewenang-wenang, dan memastikan legitimasi politik dari anggota pengganti.
Peran partai politik dalam mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan. Partai hanya memiliki kewenangan sebatas mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW), tetapi tidak dapat secara sepihak mencabut keanggotaan DPR karena mandat anggota berasal dari hasil Pemilu. Dengan kata lain, status keanggotaan tidak semata-mata ditentukan oleh keanggotaan partai, tetapi oleh legitimasi elektoral yang diberikan rakyat. Penonaktifan internal yang dilakukan oleh partai atau fraksi hanya berlaku secara administratif dalam lingkup organisasi dan tidak dapat dijadikan dasar pengosongan kursi DPR. Apabila partai memaksakan penonaktifan sebagai bentuk pemberhentian, hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Implikasi hukumnya tidak bisa dianggap ringan. Penonaktifan tanpa mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara anggota yang dinonaktifkan dengan partai politik atau lembaga DPR itu sendiri. Sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, atau bahkan Mahkamah Konstitusi jika dianggap melanggar hak konstitusional. Selain itu, praktik penonaktifan yang tidak diikuti dengan PAW dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas representasi politik di parlemen, karena kursi DPR akan menjadi tidak aktif sementara konstituen yang diwakili kehilangan representasi. Situasi ini dapat memperburuk citra DPR di mata publik, melemahkan legitimasi lembaga legislatif, dan membuka ruang politisasi penonaktifan sebagai alat tekanan politik internal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola keanggotaan DPR. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperjelas kedudukan istilah “penonaktifan” dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar memiliki definisi hukum yang tegas, ruang lingkup yang jelas, serta tidak menimbulkan multitafsir. Prosedur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, misalnya dengan mewajibkan publikasi terbuka atas setiap usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) beserta alasannya sehingga masyarakat dapat mengawasi apakah pemberhentian dilakukan sesuai ketentuan hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan, pengawasan dapat diperkuat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta mekanisme peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol konstitusional. Di sisi lain, pendidikan publik mengenai mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dan hak-hak konstitusional anggota DPR perlu digalakkan agar masyarakat memahami bahwa kursi DPR adalah mandat rakyat yang tidak boleh dikosongkan secara sewenang-wenang.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penonaktifan bukanlah sanksi hukum dalam arti formil, melainkan semata-mata tindakan administratif internal yang bersifat sementara dan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau partai politik untuk membatasi pelaksanaan tugas anggota DPR sampai ada penyelesaian lebih lanjut. Status keanggotaan tetap melekat karena penonaktifan tidak memiliki dasar konstitusional maupun yuridis formal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Satu-satunya cara yang sah untuk mengakhiri masa jabatan anggota DPR sebelum habis adalah melalui mekanisme Pemberhentian Antar Waktu yang diatur secara jelas dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 239–240 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Karena kursi di DPR merupakan mandat rakyat hasil pemilihan umum, maka setiap upaya pengosongan kursi di luar mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) berpotensi melanggar hak konstitusional anggota, mencederai prinsip kedaulatan rakyat, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengganggu stabilitas representasi politik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berdampak pada status keanggotaan harus dilakukan secara hati-hati, mengikuti prosedur konstitusional, dan diawasi secara ketat agar menjamin perlindungan hak anggota DPR serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Referensi
Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.
Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192.
Indonesia. 2015. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: DPR RI.
Mahfud MD, Moh. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009. Putusan Nomor 16/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
Penulis

Rachel Imanuela Jayadi – LP2KI XVIII